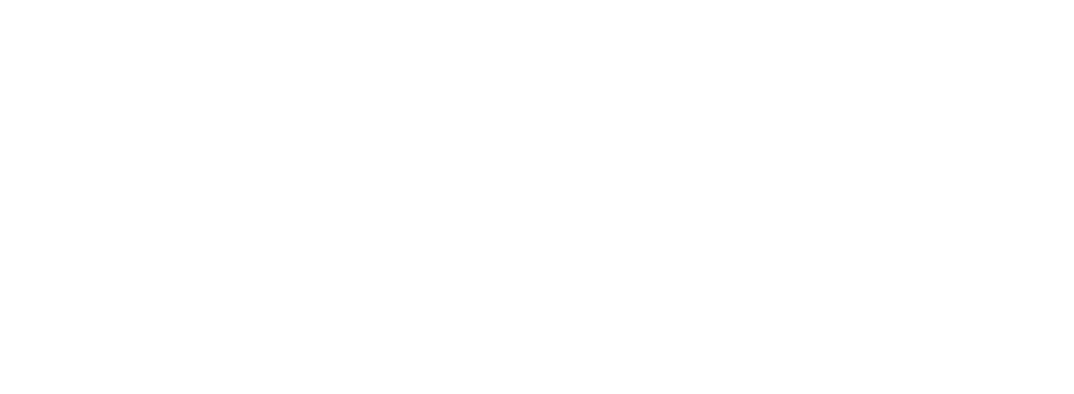Bagian 1 : Sejarah & Identitas Suku Moronene
Asal-Usul dan Persebaran
Suku Moronene
Sejarah migrasi dan pemukiman awal Moronene di Bombana
Suku Moronene dikenal sebagai salah satu suku tertua yang mendiami daratan Sulawesi Tenggara. Asal-usul leluhur Moronene menelusuri jejak panjang dari daratan Asia, tepatnya dari ras Mongoloid di kawasan Yunan, Tiongkok Selatan.
Leluhur mereka merupakan petani yang kemudian berinteraksi dengan komunitas pemburu-peramu Hoabinhian di wilayah Vietnam. Dari sana, mereka melanjutkan migrasi ke Taiwan dan Filipina, sebelum akhirnya berlayar ke arah selatan menuju Sulawesi. Kedatangan mereka di Sulawesi bagian utara membawa serta keahlian dalam membuat perahu (bangka), bertani, serta berburu. Setelah bermukim sementara, perjalanan dilanjutkan melalui Teluk Tomini, kemudian ke Sungai Tambarana di Poso, hingga wilayah Danau Matano dan Towuti. Di sepanjang perjalanan itu, lahirlah generasi-generasi baru, yang kelak menyebar masuk ke wilayah Sulawesi Tenggara, leluhur Moronene menyusuri Sungai Lasampara, Sungai Lalindu dan Konaweha, hingga mencapai Rawa Aopa.

Di sepanjang rute ini, mereka mendirikan pemukiman di berbagai tempat seperti Pohara, Lambuya, Ranoea, Labandia, hingga Pomalaa. Fakta linguistik mendukung jejak migrasi ini, di mana banyak nama tempat di Konawe, Kolaka, dan Kendari berasal dari bahasa Moronene. Pola kehidupan leluhur Moronene bersifat nomaden dan adaptif, berpindah mengikuti kesuburan lahan dan ketersediaan sumber daya alam. Beberapa kelompok bermigrasi ke pegunungan Mendoke, Hukaea, Matausu, hingga Poleang dengan menyusuri sungai dan padang savana. Di tempat-tempat baru ini mereka membentuk klan-klan yang dipimpin oleh orang yang dituakan (Miano Damotua).
Kelak, dari musyawarah para klan, terpilihlah seorang pemimpin besar (Apua) bernama Dedeangi yang membentuk pusat pemerintahan tradisional di Tangkeno Wawolesea, di hulu Sungai Laa Moronene daerah yang kaya akan tumbuhan resam, simbol kehidupan kolektif masyarakat Moronene.
Nama “Moronene” sendiri berasal dari dua kata: “moro” yang berarti serupa atau serumpun, dan “nene” yang merujuk pada tumbuhan yang menyerupai resam yang tumbuh berkelompok.
Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Moronene sangat menjunjung tinggi ikatan dengan asal-usul dan tanah warisan mereka. Kehidupan mereka sejak dahulu sangat erat dengan alam, hutan, sungai, dan gunung dianggap bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga tempat suci yang dihormati.
Menurut cerita dari para tetua, leluhur Moronene memilih lokasi yang subur dan dekat dengan sumber air (Laa Moronene) sungai. Pemukiman-pemukiman ini tumbuh dengan pola yang khas: rumah-rumah yang berdekatan, kebun di sekelilingnya, dan hutan sebagai pelindung.
Orang Moronene hidup secara kolektif, saling membantu dalam membuka ladang, membangun rumah, atau saat panen tiba. Hutan dijaga bersama karena mereka percaya bahwa ada tempat-tempat keramat yang tidak boleh dilanggar yakni:
- Inalahi Pue : Hutan inti, tempat roh dan sumber air tempat perlindungan bagi berbagai keanekaragaman hayati agar tetap lestari. Tidak boleh diganggu.
- Inalahi Popalia : Hutan sekunder/keramat. Bekas kampung dan kuburan leluhur.
- Inalahi Peuma : Hutan produktif untuk pertanian/perladangan dan perburuan.
System pengelolaan hutan dan Sistem pemukiman ini tidak hanya mengatur tempat tinggal, tetapi juga mencerminkan hubungan spiritual dan ekologis antara manusia dan alam. Wilayah dibagi dalam zona: pemukiman, kebun, hutan larangan (inalahi pue), dan tanah keramat yang tak boleh diganggu (wita popalia/inalahi popalia).
Sejarah migrasi ini bukan sekadar kisah perjalanan leluhur, tetapi menjadi fondasi cara hidup dan pandangan dunia masyarakat Moronene. Ketika orang luar datang membawa tambang atau kebijakan pembangunan tanpa memahami nilai adat, masyarakat adat
seringkali terdorong untuk mempertahankan haknya. Itulah sebabnya, banyak komunitas adat Moronene kini mulai memperkuat kembali identitas mereka dengan menggali kembali sejarah leluhur.
Bagi generasi muda Moronene, mengetahui sejarah migrasi dan pemukiman ini sangat penting. Karena dari sanalah kita belajar bahwa leluhur tidak hanya membangun rumah dan kebun, tapi juga mewariskan cara berpikir dan hidup yang selaras dengan alam. Menjaga tanah leluhur berarti menjaga kehidupan. Dengan memahami asal-usul, kita akan lebih mencintai tanah adat dan lebih bijak dalam melindungi lingkungan dari ancaman yang ada saat ini.
Hubungan dengan lingkungan: bertani, berburu, dan bertahan hidup secara Lestari
Suku Moronene sejak dulu hidup selaras dengan alam. Mereka tidak hanya memanfaatkan alam untuk kebutuhan hidup, tetapi juga menjaga dan menghormatinya. Hutan, sungai, dan tanah bukan sekadar sumber daya, melainkan bagian dari kehidupan yang harus dilestarikan. Prinsip ini membuat masyarakat Moronene memiliki pola hidup yang seimbang, penuh perhitungan, dan tidak serakah dalam mengambil dari alam.
Dalam Bertani (meuma), orang Moronene menerapkan sistem rotasi ladang dan menggunakan metode yang ramah lingkungan. Mereka membuka lahan secukupnya, tidak menggunakan bahan kimia, dan selalu membiarkan tanah beristirahat sebelum ditanami kembali. Jenis tanaman seperti jagung, ubi, dan padi ladang ditanam sesuai musim dan kebutuhan.
Setiap panen disyukuri melalui ritual adat (mewuwusoi)
sebagai wujud terima kasih kepada alam dan leluhur.
Berburu pun (melulueno) dilakukan dengan kearifan. Hanya hewan tertentu yang boleh diburu, dan jumlahnya pun dibatasi. Mereka menghindari berburu satwa yang sedang berkembang biak, dan ada hewan-hewan tertentu yang dianggap keramat dan tidak boleh disentuh. Masyarakat menggunakan alat tradisional seperti tombak (pando) atau jebakan (bengkaro, me’oho, melowu), bukan senjata api. Hal ini membuat populasi satwa tetap terjaga dan ekosistem tetap seimbang.
Selain bertani dan berburu, mereka juga mengumpulkan hasil hutan seperti madu, rotan, dan obat-obatan alami. Namun semua itu diambil dengan penuh rasa tanggung jawab. Jika mengambil rotan, mereka akan menyisakan tunas muda. Jika mengambil tanaman obat, mereka tidak mencabut habis, tapi memetik secukupnya. Inilah bentuk nyata dari praktik hidup lestari yang diwariskan turun-temurun.Hubungan yang harmonis dengan alam ini bukan hanya menjamin kelangsungan hidup mereka, tetapi juga mencerminkan pandangan hidup bahwa manusia adalah bagian dari alam, bukan penguasa alam. Filosofi ini sangat penting untuk dipahami oleh generasi muda Moronene, agar dalam menghadapi tantangan modern seperti tambang atau pembangunan, mereka tetap berpegang pada prinsip leluhur: “Jaga alam, maka alam akan menjaga kita” Dagaho wonua, wonua nta’pokontiorako.